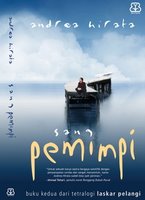Bahagianya, berjalan di tengah merah putih di sekelilingku. Bendera kecil bergelantungan di tali-tali, membentang di jalan-jalan masuk gang. Di bawahnya, jalan aspal yang hitam di beri batas luar warna putih. Umbul-umbul turut serta mewarnai, ada kain umbul warna merah, hijau, biru, kuning, dan putih. Tak lupa, lampu kerlap-kerlip yang menyapa. Semuanya berpadu rancak menyambut siapapun orang yang lewat.
Bahagianya, berjalan di tengah merah putih di sekelilingku. Bendera kecil bergelantungan di tali-tali, membentang di jalan-jalan masuk gang. Di bawahnya, jalan aspal yang hitam di beri batas luar warna putih. Umbul-umbul turut serta mewarnai, ada kain umbul warna merah, hijau, biru, kuning, dan putih. Tak lupa, lampu kerlap-kerlip yang menyapa. Semuanya berpadu rancak menyambut siapapun orang yang lewat.
Sudah 61 tahun lalu ternyata, bangsa ini merdeka. Padahal, suara Bung Karno masih saja terngiang jelas, selalu menemani kesendirian. Memberi pijar harapan, dalam semua keterbatasan hidup. Padahal, suara-suara mesiu, dan bau-bau ledakan masih tak juga hilang dari ingatan. Dan yang masih sangat jelas, pekik-pekik “Merdeka…Merdeka, Merdeka!”. Melihat seolah semua penduduk negeri ini berhamburan keluar, bersatu, tak peduli siapapun dia, akan dengan bangga saling berkata dan berjabat tangan, “kita sudah merdeka bung..!”. Jatuh air mata ku mengenangnya.
Berarti, sudah 61 tahun pula bangsa ini membangun. Demi kesejahteraan rakyat, itu tujuan pembangunan seperti yang pernah dikatakan Bung Karno di Lapangan Benteng menjelang peringatan kemerdekaan ke-10. Sederhana saja, membangun artinya membuat rakyat sejahtera, tidak sulit hidupnya, tidak perlu mengantri bahan pangan lagi, tidak usah pula meringis kelaparan, hidup tenang, punya garapan sawah dan anak-anak yang bisa bersekolah.
Karena menurut para cerdik-pandai perjuangan kemerdekaan dulu, Indonesia adalah bangsa yang kaya. Dalam kesendirian kami, pejuang-pejuang ini berjalan menyiisir hutan demi hutan, sawah, sungai, dan gunung, tak satupun tanah negeri ini yang kering, tak menghasilkan apa-apa. Di saat-saat malam penjagaan di pos, ditemani sebuah radio peninggalan meneer mandor tebu, lirik lagu Ismail Marzuki inilah yang selalu sering diputar, memberi hiburan bagi kami yang selalu penuh harap..
Tanah air-ku, Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darah-ku yang mulya
Yang kupuja s’panjang masaTanah airku aman dan makmur..
Ah, itu lah cerita masa lalu. Masa kami, orang-orang tua mendirikan bangunan bangsa ini. Ya..bangunan bangsa, bukan bangunan Jakarta, Surabaya atau Bandung. Karena dimana-mana, di atas tanah bernama Indonesia, tak peduli apakah Bung Karno, Bung Hatta atau Bung Sjahrir tahu atau tidak, kami merasa harus membangun Indonesia, negeri tempat anak dan cucu kami akan lahir.
Tidak susah, tinggal angkat senjata. Ambil parang, buat tombak, atau rampas senjata lawan. Tembak atau tertembak, mati atau sekarat, tak jadi soal. Bukankah semua sudah digariskan? Kalaupun tiada, mati kami mulia karena perjuangan. Tuhan tak akan salah melihat kami.
Tapi ternyata, membangun tak semudah mengangkat senjata. Membangun butuh orang pintar. Dan seperti kata ibu-ku, semakin orang pinter, makin mudah keblinger. Kami tak paham, istilah-istilah yang digunakan orang-orang pintar negeri ini. Pemberdayaan, globalisasi, atau reformasi.
Katanya pemberdayaan berasal dari kata daya. Jadi, apakah pemberdayaan berusaha menjadikan orang berdaya, punya daya? Jadi, selama ini rakyat tidak punya daya? Lho, tenaga yang dipakai buat mengidupi anak istri, itu kan daya juga. Lalu, globalisasi. Aku malah jadi ingat gombalisasi. Sama seperti musang-musang pribumi yang jadi cecunguk Belanda, bermuka manis di depan, tapi ternyata gombal. Reformasi katanya perubahan pelan-pelan. Kalau kemudian repot-nasi, apa itu pelan-pelan juga? Tak ngerti aku dengan orang-orang pintar ini. Bung Hatta yang berkali-kali pergi ke negeri Belanda sana, rasanya masih bisa berbicara kepada kami-kami ini.
Kalau sekarang, hidup kami tak dikenal, kami juga tidak akan marah. Kami bukan anak-anak muda zaman sekarang. Berteriak-teriak, istilahnya demonstrasi, menuntut ini itu, bakar sana sini. Tapi, urusan gaya hidup, sama saja. Makan cukup, necis dengan kaos dan celana dari negeri Amerika. Apa mereka pernah merasakan jadi orang-orang yang mereka bela? Mana ada cerita, berjuang demi sesuatu yang belum pernah ia rasakan.
Kalau sekarang, banyak orang yang sikut-sikutan ingin menjadi pemimpin, terkenal, dihormati, atau kaya, kami pun tak perlu ikut-ikutan atau berkata bodoh, ”kami yang harusnya menjadi orang yang paling dihormati, karena bangsa ini tak akan tanpa kami”. Walaupun, mereka mengatasnamakan pihak-pihak yang baik, sebagai penerus perjuangan, generasi muda, harapan baru, penyemai kebenaran, pembawa kesejahteraan. Dan semuanya mengatakan demi rakyat, atau umat. Mereka harusnya melihat, apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa ini? Apa mereka serta merta mau mengambil nasib negeri ini, dengan dalih menyelamatkan masa depan?
Rasa-rasanya, pendiri dan pejuang bangsa ini tak pernah gontok-gontokan, dari banyak macam golongan pun. Bangsa ini punya sejarah. Jangan dikira hanya lahir kemarin sore dan kalian berhak mengaturnya, demi apapun yang kalian punya. Sekali lagi, kami pun tak perlu ikut-ikutan yang seperti itu.
Walaupun kami hanya diingat di saat-saat hari kemerdekaan, dengan bunga, ucapan atau bantuan hidup sekedarnya, tak pernah menjadikan kami bosan untuk selalu mencintai negeri ini. Meskipun sekarang, sangat sedikit orang yang berteriak ”Merdeka!” dan paham semangat di dalamnya, kami tak juga merasa perlu untuk membenci anak-anak kami. Bahkan untuk yang sangat sederhana, saling berucap ”Selamat Hari Merdeka” pun jarang. Padahal dalam akhir puasa, cucuku selalu ikut berdesakan berkirim pesan lewat hp. Lalu, lampu hias, jalan berbatas putih, bendera bergelantungan dan umbul-umbul serasa hening, tak berucap merdeka.
Kami cinta negeri ini. Disini tempat lahir kami, dan disini pula kami akan menutup mata. Rasanya, Bung Karno dan Bung Hatta hadir kembali membacakan teks proklamasi tanggal 17 esok. Dan ingin sekali, esok pagi...pagi-pagi sekali aku membuka pintu rumah. Mengirup udara 17. Lalu berteriak parau nan lantang, selantang-lantangnya...MERDEKA!.
 Dulu, kami sempat memberikan nama, Acapela. Kenapa? Karena beberapa orang dari 5 orang yang tinggal disitu suka menyanyikan sebuah genre lagu dengan acapela, mengandalkan kombinasi bunyi suara. Lalu ada yang menyebut pondok derita. Tidak tahu, apa maksud pondok derita itu.
Dulu, kami sempat memberikan nama, Acapela. Kenapa? Karena beberapa orang dari 5 orang yang tinggal disitu suka menyanyikan sebuah genre lagu dengan acapela, mengandalkan kombinasi bunyi suara. Lalu ada yang menyebut pondok derita. Tidak tahu, apa maksud pondok derita itu.![[ blog of mine ]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGbEjE-4gO5g7lNz5xCNx4DBrhwST6FXUiGdZYKDCniwljveKLJ5v_0jggj-8L_LVh1rxveS9yzgimz0YJoTPT0MxOzjn-5yq-z-FQgftLgJ7Q-6RPVzQeQXGLQuKeeDmV8L453g/s830/trianshadow.jpg)