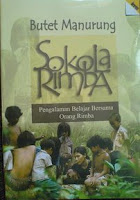Apa yang terbayangkan segera dengan negeri bernama Afganistan? Hancur, porak poranda sisa agresi Amerika demi memburu Osama bin Laden yang tak kunjung ditemuinya. Dan pasca agresi itu, praktis wajah Afganistan kembali hilang ditelan bumi penuh konflik timur tengah lainnya.
Namun sebenarnya, apa yang tersingkap dalam media-media yang memberitakan kondisi Afaganistan belum tentu menggambarkan kondisi (dan psikologis) Afganistan yang sesungguhnya. Dan lewat sebuah buku memoar perjalanan, Latifa dan Asne Seierstad masing-masing memberi sudut pandang lain dari kehidupan Afganistan.
My Forbidden Face (Wajah Terlarang-WT) karya Latifa,sungguh-sungguh sangat bagus dalam mendeskripsikan gejolak perasaan perempuan Afgan terutama semasa Taliban yang menerapkan ‘syariat Islam konservatif’ (yang menurut saya berlebihan),diantaranya melarang perempuan bekerja, sekolah dan bahkan keluar rumah tanpa orang yang menemani dengan penutup badan-kepala (burqa). Sednagkan laki-laki harus mempunyai jenggot panjang serta memakai baju jubah. Tidak boleh aktivitas malam, semua TV, media dilarang kecuali siaran agama-propaganda, tidak ada campur laki-laki perempuan di semua urusan, peredaran buku diawasi dan jika melanggar maka polisi pun akan menyeret ke pengadilan agama.
Latifa, seorang wanita asli Afgan yang menghabiskan waktu disana hingga usia 16 tahun saat-saat akhir kekuasaan Taliban, sempat menjadi guru bagi perempuan-perempuan kecil yang dilarang sekolah di sekolah formal dengan sembunyi-sembunyi menggunakan rumah keluarganya. Latifa kemudian ’hijrah’ ke Paris didukung ibu dan keluarganya untuk menyuarakan suara perempuan Afgan di dunia internasional.
Ibunya sendiri adalah dokter yang dilarang bekerja di rumah sakit sejak Taliban, dan akhirnya bersama Latifa membangun klinik sendiri di bagian belakang rumahnya tanpa sepengetahuan Taliban, karena tidak tega melihat pasien-pasien perempuan yang tidak pergi ke RS akibat semua dokternya laki-laki.
Sedangkan Asne, jurnalis Norwegia yang meliput ke Afgan dalam detik-detik Taliban jatuh lalu bertemu dengan Sultan Khan, seorang saudagar buku dan kemudian tinggal serumah bersama keluarganya selama 3 bulan untuk merasakan penuh kehidupan sebuah keluarga Afgan.
Saudagar Buku dari Kabul (The Bookseller of Kabul) - SB, lebih menggambarkan potret keluarga di tengah banyak perubahan kekuasaan di Afgan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang dunia Afgan saja, tapi juga wilayah-wilayah di sekitarnya yang turut mempengaruhi kondisi politik-keamanan di Afgan. Menyusuri wilayah pesisir sambil mengetahui kondisi sosial-politiknya tentu lebih membuka mata tentang apa yang terjadi di Afgan.
Ide sentral kehidupan keluarga khas Afgan patut diacungi jempol. Pendeskripsian yang baik tentang posisi kepala keluarga yang sangat kuasa, tugas istri, ibu kepala keluarga, anak dan susunan lain yang membentuk keluarga. Layaknya sebuah keluarga, maka banyak konflik pun mendera disana apalagi dengan tangan besi Sultan yang sangat keras dan tanpa kompromi kepada keluarga.
Lalu lagi-lagi tentang perempuan Afgan yang penuh kisah sendu itu seperti dalam buku WT. Jika WT lebih banyak pada aktivitas sosial perempuan yang terkengkang, maka SB berkali-kali menggambarkan tentang ketidakperdayaan perempuan Afgan dalam meimilih pasangan hidupnya. Sebenarnya laki-laki pun demikian, namun laki-laki lebih bisa mengatakan keinginannya lalu menyerahkan hak melamar kepada ibu atau saudara perempuan. Sedang si perempuan, hanya bisa diam dan menerima apa kata ibu atau keluarganya yang biasa hanya atas pertimbangan materi menjual anak gadisnya.
Kisah keluarga saudagar diakhiri dengan sebuah sketsa cinta menyedihkan, antara Leila (adik Sultan) yang disukai Karim (seorang pemuda mapan) dan akhirnya kandas karena’budaya’ terkungkungnya seorang wanita Afgan terutama sejak Taliban dan masih berbekas sesudahnya. Menurut Leila, perempuan Afgan itu tidak punya rasa, tidak bisa merasakan apa-apa karena tidak terbiasa merasakan apa-apa. Dia tidak punya rasa karena tahu dia tak boleh punya perasaan. Jadi, apakah mempunyai perasaan dan memperjuangkannya adalah tabu bagi seorang perempuan?
***
Buku bagaimanapun adalah media yang sangat baik untuk menyuarakan hati nurani.  Dan buku memoar, buku yang ditulis sebagai catatan perjalanan dan liku-likunya atas sebuah negeri bernama Afganistan ibarat suara hati nurani tercekik di balik kerudung Islam konservatif. Wajah Terlarang atau Saudagar Buku dari Kabul telah menjadi bukti eksistensi sebuah buku memoar, menampilkan sisi lain kehidupan Afgan, lebih membuka mata dunia dan kemudian memahami apa yang terjadi disana.
Dan buku memoar, buku yang ditulis sebagai catatan perjalanan dan liku-likunya atas sebuah negeri bernama Afganistan ibarat suara hati nurani tercekik di balik kerudung Islam konservatif. Wajah Terlarang atau Saudagar Buku dari Kabul telah menjadi bukti eksistensi sebuah buku memoar, menampilkan sisi lain kehidupan Afgan, lebih membuka mata dunia dan kemudian memahami apa yang terjadi disana.
Semua dalam kehidupan penuh pilihan. Tapi tentu tidak ada orang yang memilih dalam kehidupan penuh ketertindasan dan keterkengkangan. Karena perasaan bebas dan bertanggung jawab atas apapun yang dipilihnya itu, adalah bagian utama dalam kehidupan manusia.
hidup selalu punya akhir
tidak perlu lagi ditindas
jika ketundukan adalah prasyarat hidup
aku tidak butuh hidup macam ini
dalam perbudakan,
bisa saja terjadi hujan emas
dan akan kukatakan pada langit
hujan ini tak dibutuhkan
[Latifa]
![[ blog of mine ]](http://3.bp.blogspot.com/-hUUqkUUXufQ/UVt7DcdguGI/AAAAAAAABa0/ha3UfCENYuc/s830/trianshadow.jpg)